“Ya, jangan pernah ajari anak berbohong”. Judul yang provokatif. Tak ada orang yang mau anaknya menjadi pembohong. Semua ingin punya anak jujur. Tahukah Anda, justru kitalah yang selama ini, sadar atau tidak, telah mengajari anak-anak berdusta?
Peristiwa ini sudah lebih dari setahun berlalu. Entah mengapa, sampai sekarang saya tak pernah benar-benar bisa melupakannya. Saya menyesal. Kesal. Oh, seandainya waktu bisa berputar, saya pasti akan memperbaikinya.
Hari itu seharusnya menjadi hari yang besar untuk “si sulung” Safira. Berkali-kali dia menyatakan keraguannya apakah dia berani atau tidak mengikuti lomba tartil. Dia dipilih ustadzahnya untuk mewakili TPA-nya dalam perlombaan itu. Tentu saja saya menyemangatinya.
“Hebat dong. Ikut saja, Mbak Safira pasti bisa”.
“Nanti kalau kalah bagaimana ayah?”
“Ini bukan soal menang kalah, anakku. Ini soal belajar tampil depan umum. Ini latihan keberanian. Mbak Safira hebat lho bisa terpilih?”. Saya terus memompa agar Safira lebih pede. Di mata saya dia sungguh luar biasa. Waktu itu, kelas 1 SD, sudah lancar baca Alqur’an. Suaranya pun merdu.
Sayang di hari H, kami berdua pas sama-sama sibuk. Istri ada jadwal pengajian, sudah sejak awal minta saya yang nemani lomba. Mendadak saya pun harus pergi untuk sebuah urusan yang sangat penting. Saya merasa aman karena Safira ditemani para ustadzahnya.
“Bagaimana tadi lombanya, Mbak?”
Saya lupa jawaban pasti Safira siang itu. Kesan yang saya tangkap dia cuma tak yakin bisa menang. Saya pun tak berusaha mengejarnya karena bukan itu tujuan ikut perlombaan.
Seminggu berselang, ada tetangga yang cerita pada “staf ahli” kami kalau saat itu Safira tidak jadi tampil. Safira tentu saja grogi karena ketahuan selama ini membohongi kami soal lomba itu.
“Ibu, maaf ibu. Aku kemarin itu nggak jadi lomba”. Safira menangis keras-keras menunjukkan penyesalannya telah berbohong pada kami. Belakangan saya tahu, dia peserta nomor urut 30-an. Mungkin lelah menunggu, pas giliran tampil malah mogok.
Batal lomba bukan problem besar. Bohongnya itu yang serasa menampar keras pipi saya. Mengapa anakku tak jujur saja saat ditanya soal lomba? Mengapa tak bilang batal tampil karena capek? Alasan yang bagus. Kami pasti tak akan memarahinya. Duhh..
Saya berhari-hari mikir, mengapa anak berbohong pada orang tua. Itu bukan ajaran kami. Setahu saya, hanya sekali Safira berdusta. Mengaku sudah sholat subuh, tapi mukenanya masih terlihat rapi seperti malam sehabis Isya’. Ibunya menasehati, “Nggak boleh bohong lho”. Dia menangis, menyesal. Bagi saya itu cukup. Dan dia terlihat tak pernah mengulanginya lagi.
Beberapa hari kemudian saya tahu penyebabnya. Hari itu saya ingin pergi berduaan dengan Safira. Tak boleh ada yang ikut, termasuk istri. Saya sedang berusaha membangun hubungan satu persatu dengan masing-masing anak. Tapi rencana ini bocor, adiknya ingin ikut.
“Yah, dibohongin aja, bilang aku mau ke eyang. Nanti ayah jemput”
“Nggak boleh bohong Safira”, saya tak setuju idenya.
“Khan nggak apa-apa ayah. Biar adik nggak minta ikut”.
Safira rupanya meniru “trik” staf ahli kami di rumah saat menenangkan anak-anak yang rewel. Kalau saya dan istri mau keluar rumah dan mereka minta ikut, staf ahli bilang, “Ayah ibu khan mau kerja, biar dapat uang buat bayar sekolah”. Saat itu padahal saya tidak sedang hendak bekerja. Atau kalau anak-anak merengek minta dibelikan kue, staf ahli langsung menjawab, “Khan tokonya masih tutup”. Selalu saja ada jawaban spontanitas dari staf ahli untuk menenangkan anak-anak di rumah.
Awalnya saya cuek saja. Tapi setelah tahu dampaknya bahwa “boleh bohong asal”, maka saya melarang staf ahli bikin akal-akalan untuk membohongi anak. Dengan alasan apapun.
Kalau kami berdua ingin sekedar malam berdua di luar rumah dan anak-anak mau ikut, saya bilang, “Ayah ibu cuma mau berduaan malam ini”.
“Curang. Mengapa aku gak boleh ikut?”. “Mengapa sih ayah kok cuma mau ajak ibu?” satunya protes juga. Pokoknya rame.
“Nak, ayah ibu cuma ingin berdua”.
“Mengapa sih cuma berdua?”
“Ayah ibu mau omong-omong, jadi berdua”.
“Memang ngomongin apa aja sih?” Tetap protes.
“Ya banyaklah. Tentang sekolah kalian. Bagaimana anak-anak jadi tambah pinter. Itu urusan orang tua. Sudah, semua tinggal di rumah, nanti ayah belikan oleh-oleh”.
Kami pergi, anak-anak (mungkin) masih dongkol. Mungkin jadi nangis keras-keras setelah kami berangkat. Atau sebentar-sebentar HP berbunyi, “Kok lama sih nggak pulang-pulang?”. Huh, capek deh si anak ini.
Dulu, saya tak ingin “menyakiti” anak-anak. Maka saya pun membiarkan staf ahli “kreatif” menyelesaikan problem rumah tangga ini. Mungkin lebih enak kalau saya bilang, “Ayah lagi kerja”. Atau, “Ayah nganter ibu sebentar”. Cari-cari alasan khan gampang. Anak kecil mudah dibohongin.
Sekarang saya tegas menegakkan kejujuran. “Nggak boleh ikut, ini urusan orang tua”. Saya juga nggak bisa bohong toko tutup kalau anak merengek minta kue, karena mereka tahu beberapa puluh meter dari rumah kami ada swalayan yang buka 24 jam. Saya jadi lebih tegas, “Kemarin khan sudah beli kue. Sekarang uang ditabung. Kalau masih lapar, itu ada makanan di meja”. Atau ditunda dulu, “Nanti hari minggu jalan-jalan boleh ikut belanja. Sekarang nggak boleh beli kue”. Jujur, meski menyakitkan. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang kita membohongi anak khan?
Saya terkesan dengan teman saya, Habe Arifin, seorang jurnalis di Jakarta. Saat itu kami berdua menjaga sepeda yang akan dibagikan ke siswa dari kalangan tak mampu (lihat program kami di www.sepedauntuksekolah.org).
Seorang anak merengek minta sepeda tersebut. Ibunya terlihat kewalahan dan mulai membujuknya.
“Di rumah khan sudah ada!”
“Pokoknya, aku mau yang ini”.
“Nanti, pulang dari sini ibu belikan”.
“Nggak. Aku maunya sekarang!”
“Iiihh… anak, bandel banget. Nggak nurut kalau dikasih tahu”.
Saya memperhatikan saja ibu dan anak yang berdebat hebat di depan saya. Ini pelajaran menarik pastinya. Si anak mulai mengamuk, tas ibunya ditarik-tarik. Teriak-teriak. Dalam hati saya mbatin, “Sangat liar anak ini”. Tas tangan Mas Toto Sugito (juga kolega saya, ketua umum Bike To Work) yang berada di meja diambil si anak dan kemudian dilemparkan ke lantai.
“Anak saya ya gini ini, Pak. Kalau rewel, HP saja dibanting”. Ibunya tidak mampu mengatasi “keberingasan” anak, dan mulai berbohong, “Heh.. Nak, ini sepeda rusak. Nggak bisa dipakai. Tanya saja sama bapaknya sana?”. Ibu itu berharap saya dan Mas Habe mendukung statemennya.
Tapi Mas Habe tidak sependapat. Dia ngomong keras. “Dik, ini sepeda masih baru. Jelas bisa dipakai. Namanya juga sepeda baru. Masih dibungkus tuh. Tapi adik harus tahu, ini bukan sepeda kamu. Ini sepeda baru, tapi ini bukan untuk kamu. Mengerti?” Tegas. Tanpa basa basi. Mas Habe lalu menasehati si ibu, tak kalah kerasnya, “Bu, anak itu nggak boleh dibohongi. Harus dikatakan apa adanya”.
Sejurus kemudian, si ibu mulai menyeret anaknya. Tak mau kalah, anak laki-laki itu meronta. Memukul. Teriak-teriak.
Saya sungguh kasihan. Shock melihat anak kecil bisa “ngamuk” seperti itu. Mungkin dia terbiasa dibohongin. Jadi rayuan ibunya sudah tak mempan. Pikirnya, kalau ibu janji nanti mau dibelikan toh paling juga bohong (lagi).
Saya salut dengan keberanian Mas Habe mengingatkan si ibu agar tak gampang membohongi anaknya. Kejadian inilah yang menginspirasi saya untuk menuliskan catatan elektronik ini. Karena saya pernah mengalaminya sendiri. Dibohongi anak sungguh tak enak. Jika Anda tak ingin mengalami nasib seperti saya, pliss… jangan jangan jangan dan jangan pernah berbohong pada anak. Katakan yang sebenarnnya meski menyakitkan. Kelak, anak juga akan makin mengerti alasan yang Anda kemukakan. (www.baitijannati.wordpress.com)

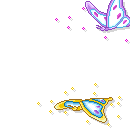
0 komentar:
Posting Komentar